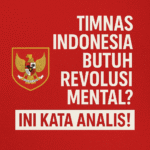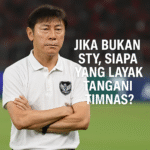Pondasi Proyek 2026: Visi Besar Shin Tae-yong
Sejak awal ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong (STY) telah membawa pendekatan berbeda yang lebih sistematis dan jangka panjang. Tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, STY menanamkan filosofi permainan modern, mengedepankan transisi cepat, pressing tinggi, serta pengembangan fisik dan mental yang tangguh—sesuatu yang belum menjadi budaya dominan di sepak bola Indonesia sebelumnya.
Target utama dari proyek jangka panjang ini adalah membawa Timnas Indonesia tampil kompetitif di level Asia, bahkan mencuri tiket ke Piala Dunia 2026 yang kini memberikan peluang lebih besar dengan format 48 tim. Dalam beberapa tahun terakhir, STY sudah menunjukkan progres signifikan, seperti finalis AFF 2020, tampil impresif di Kualifikasi Piala Asia 2023, dan kini membawa Timnas menembus babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia.
Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah semua fondasi ini cukup kuat untuk menopang ambisi besar menuju 2026? Banyak indikator yang bisa dianalisis untuk menjawabnya. Mulai dari kualitas liga domestik, kesiapan infrastruktur pemain muda, keberlanjutan filosofi permainan, hingga kestabilan manajemen federasi.
Dalam konteks proyek STY, pendekatan jangka panjang yang diterapkannya patut diapresiasi. Tapi sebagaimana proyek besar lainnya, eksekusi dan konsistensi tetap menjadi kunci. Artikel ini akan mengupas secara bertahap komponen penting yang menentukan apakah Timnas Indonesia memang sedang berada di jalur yang tepat menuju panggung global.
Permasalahan Liga dan Kualitas Kompetisi Domestik
Salah satu tantangan utama dalam proyek STY adalah kualitas kompetisi domestik, yakni Liga 1 dan Liga 2. Meski dari sisi popularitas Liga 1 terus meningkat, namun aspek teknis dan pembinaan pemain lokal masih jadi sorotan. Banyak pemain yang tampil inkonsisten, kurang jam terbang internasional, dan belum terbiasa bermain dalam sistem kolektif yang intens.
Shin Tae-yong sendiri beberapa kali mengkritik kondisi liga, terutama soal intensitas permainan dan disiplin taktik yang rendah. Ia bahkan menyebut banyak pemain Indonesia kesulitan beradaptasi dengan sistem pressing ketat yang ia terapkan karena belum terbiasa dari level klub. Ini tentu menjadi alarm keras bagi federasi dan operator liga untuk melakukan reformasi kompetisi.
Selain itu, jumlah menit bermain pemain muda di Liga 1 masih minim. Banyak klub yang lebih memilih mendatangkan pemain asing atau pemain senior daripada memberi panggung bagi pemain U-23. Padahal, regenerasi adalah inti dari proyek 2026. Tanpa jam terbang reguler di level klub, pemain muda sulit menunjukkan performa optimal saat membela timnas.
Dalam konteks ini, proyek STY membutuhkan dukungan konkret dari ekosistem sepak bola nasional. Tidak bisa hanya mengandalkan pelatih. Liga harus ditingkatkan secara sistemik—baik dari segi kualitas pelatih lokal, infrastruktur klub, hingga sistem kompetisi yang mendorong pengembangan bakat muda secara konsisten.
Regenerasi, Diaspora, dan Naturalisasi: Solusi atau Tambal Sulam?
Dalam proses membentuk tim kompetitif menuju 2026, STY kerap mengombinasikan pemain lokal muda dengan pemain diaspora dan naturalisasi. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Rafael Struick menjadi pilar penting. Strategi ini memang memberikan dampak instan dalam peningkatan kualitas tim, terutama dari segi taktik dan mental bertanding.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah: apakah strategi ini bagian dari pembangunan jangka panjang atau sekadar solusi tambal sulam? Ketergantungan pada pemain diaspora bisa berisiko jika tidak diimbangi dengan pengembangan lokal yang seimbang. Kita harus memastikan bahwa naturalisasi bukan jalan pintas, tapi bagian dari roadmap regenerasi yang sehat dan terukur.
Di sisi lain, pemain muda lokal seperti Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho menunjukkan potensi besar. Tapi mereka membutuhkan lebih dari sekadar panggilan ke timnas. Mereka butuh lingkungan kompetitif yang menantang dan program pengembangan berkelanjutan agar bisa bersaing dengan pemain diaspora yang sudah terbiasa bermain di liga elite Eropa.
Shin Tae-yong sendiri kerap menekankan pentingnya mental dan kedisiplinan dalam regenerasi pemain. Ia secara terbuka menyoroti mental lemah sebagian pemain lokal ketika menghadapi tekanan besar. Ini menunjukkan bahwa regenerasi bukan cuma soal usia muda, tetapi kesiapan holistik seorang pemain—fisik, teknik, taktik, dan mental.
Apakah Kita di Jalur yang Tepat?
Jika menilai secara objektif, proyek jangka panjang Shin Tae-yong menunjukkan progres yang nyata. Timnas Indonesia kini tak lagi menjadi bulan-bulanan di level Asia, melainkan tim yang mulai disegani. Gaya bermain lebih modern, fisik pemain meningkat, dan kedisiplinan mulai menjadi budaya baru. Semua ini merupakan langkah penting menuju target besar di 2026.
Namun, progres ini belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang solid. Kualitas liga masih jauh dari ideal, regenerasi masih belum stabil, dan peran federasi kadang inkonsisten dalam mendukung roadmap jangka panjang. Shin Tae-yong ibarat seorang arsitek yang bekerja keras, namun masih kekurangan bahan bangunan dan bantuan dari para tukang lainnya.
Untuk benar-benar berada di jalur yang tepat menuju 2026, diperlukan sinergi antara pelatih, federasi, klub, dan stakeholder lainnya. Pembinaan usia dini harus diperkuat, liga domestik harus dinaikkan levelnya, dan program naturalisasi harus tetap selektif serta terukur. Tanpa itu semua, proyek STY bisa mandek di tengah jalan—bukan karena gagal secara taktik, tetapi karena gagal mendapat dukungan sistemik.
Dengan waktu yang semakin sempit menuju Piala Dunia 2026, momentum ini harus dijaga. STY telah membuka jalan. Kini saatnya semua pihak memastikan bahwa jalan itu tidak berujung buntu, melainkan mengarah ke prestasi yang selama ini hanya jadi mimpi panjang sepak bola Indonesia.